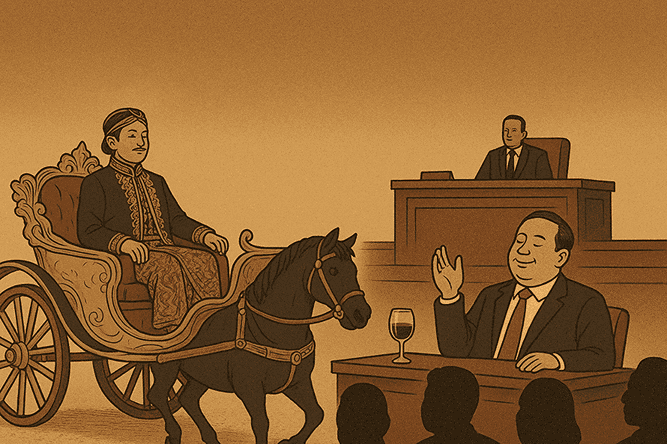Menyambut (Isu) Pergantian Kapolri
9 jam lalu
Usulan yang juga perlu dipertimbangkan adalah membatasi masa jabatan Kapolri maksimal dua tahun, supaya tidak jadi alat politik.
***
ISU pergantian Kapolri mulai berhembus kencang. Presiden Prabowo dikabarkan sudah menyiapkan dan mengusulkan ke DPR nama baru untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Jika benar, maka pergantian ini akan menjadi momen krusial dalam perjalanan Polri sekaligus ujian pertama bagi komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi serius terhadap institusi kepolisian.
Publik menyambut isu ini dengan antusias, sebab kepercayaan terhadap kepolisian belakangan kian terkikis. Bukan hanya karena sejumlah kasus besar yang berlarut-larut tanpa kepastian hukum, tetapi juga karena kerancuan yang ditimbulkan oleh pucuk pimpinan Polri sendiri.
Selama kepemimpinan Jenderal Sigit, yang menjabat Kapolri sejak 27 Januari 2021 pada era Presiden Jokowi, polisi kerap dituding bermain di wilayah abu-abu antara hukum dan politik. Dugaan keterlibatan aparat dalam pengaturan kasus, pengabaian pada perkara yang melibatkan orang dekat kekuasaan, hingga keberpihakan terselubung pada partai politik tertentu semakin memperkuat stigma buruk itu. Tidak heran muncul istilah sinis “Partai Coklat”, yang menggambarkan bagaimana Polri dianggap telah menjelma menjadi kekuatan politik tersendiri.
Masalah utamanya bukan sekadar pada pribadi Kapolri, melainkan pada sistem yang memungkinkan seorang pejabat setingkat Kapolri bertahan terlalu lama tanpa pengawasan ketat. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, jabatan Kapolri tidak memiliki batas masa jabatan yang jelas. Satu-satunya rambu hanyalah usia pensiun yang ditetapkan maksimal 60 tahun. Artinya, seorang Kapolri bisa menjabat hingga lima tahun atau bahkan lebih, selama Presiden menghendaki. Pola serupa berlaku untuk Jaksa Agung maupun Panglima TNI yang diatur dalam UU Kejaksaan dan UU TNI.
Ketiadaan pembatasan inilah yang berbahaya. Semakin lama seseorang bercokol di jabatan strategis, semakin besar pula peluangnya untuk mengakumulasi kekuasaan, membangun jejaring politik, dan menjadikan institusinya alat kekuasaan.
Kapolri yang terlalu lama menjabat bisa menjelma menjadi perisai politik presiden, Jaksa Agung berisiko menjadi pedagang kasus, dan Panglima TNI bisa kembali tergoda memainkan peran politik ala dwifungsi militer. Semua ini adalah ancaman serius bagi demokrasi yang kita rawat dengan susah payah.
Karena itu, reformasi struktural sangat mendesak. Salah satu usul yang perlu dipertimbangkan adalah membatasi masa jabatan Kapolri maksimal dua tahun. Bukan lima tahun. Dua tahun sudah cukup untuk menyusun prioritas, mengeksekusi program, sekaligus memberi kesempatan regenerasi yang sehat.
Setiap dua tahun, presiden bersama DPR dapat melakukan evaluasi ketat: apakah Kapolri benar-benar menegakkan hukum secara profesional, atau justru condong ke kepentingan politik tertentu. Dengan pola ini, sirkulasi kepemimpinan akan berjalan alami, dan Polri tidak lagi bergantung pada figur tunggal yang terlalu dominan.
Bercermin ke Luar Negeri
Jika menengok ke luar negeri, praktik pembatasan dan pengawasan ketat terhadap pucuk pimpinan kepolisian sudah lazim dilakukan. Di Inggris, Chief Constable dipilih untuk masa bakti tetap yang relatif singkat, dengan evaluasi rutin dari otoritas independen.
Di Amerika Serikat, Direktur FBI memang diberi masa jabatan sepuluh tahun, tetapi setiap tindakannya diawasi ketat oleh Kongres, dan ia bisa diberhentikan langsung oleh Presiden bila kehilangan kepercayaan publik.
Sebaliknya, di sejumlah negara Amerika Latin, ketiadaan pembatasan justru membuat polisi terjebak dalam pusaran politik rezim, bahkan terlibat dalam represi terhadap rakyat. Indonesia jelas tidak boleh mengulang kesalahan itu.
Memutus Mata Rantai Politik
Selain pembatasan masa jabatan, ada satu hal lagi yang tak kalah penting: melarang mantan pejabat strategis seperti Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung menduduki jabatan tinggi negara, termasuk kursi menteri dalam kabinet. Aturan ini krusial untuk memutus rantai politik balas budi.
Kita terlalu sering menyaksikan pola lama: seorang Kapolri atau Panglima TNI baru pensiun, beberapa bulan kemudian sudah dilantik menjadi menteri. Publik pun mafhum bahwa loyalitas semasa menjabat dibayar dengan kursi politik setelah purna tugas. Pola semacam ini bukan hanya mencederai netralitas institusi, tetapi juga mengikat Polri, TNI, maupun Kejaksaan pada kepentingan rezim yang sedang berkuasa.
Menyambut isu pergantian Kapolri seharusnya bukan sekadar menyambut pergantian nama. Momentum ini harus dimaknai sebagai pintu masuk bagi reformasi struktural yang lebih mendasar. Presiden Prabowo punya peluang emas untuk mengembalikan marwah Polri sebagai institusi yang benar-benar profesional, netral, dan hanya tunduk pada hukum. Tapi peluang itu akan terbuang sia-sia jika pergantian hanya berhenti pada rotasi jabatan tanpa perombakan sistem.
Publik menunggu langkah nyata. Bila Presiden hanya mengganti Kapolri tanpa menyentuh akar masalah, maka istilah “Partai Coklat” akan tetap hidup, dan kepercayaan rakyat terhadap kepolisian tidak akan pernah pulih. Reformasi bukan soal siapa yang duduk di kursi Kapolri, tetapi bagaimana jabatan itu dikawal agar tidak lagi menjadi alat kekuasaan.
Penulis Indonesiana l Veteran Jurnalis
4 Pengikut

Menyambut (Isu) Pergantian Kapolri
9 jam lalu
DPR: Dari Rumah Rakyat ke Panggung Artis
Minggu, 7 September 2025 09:43 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan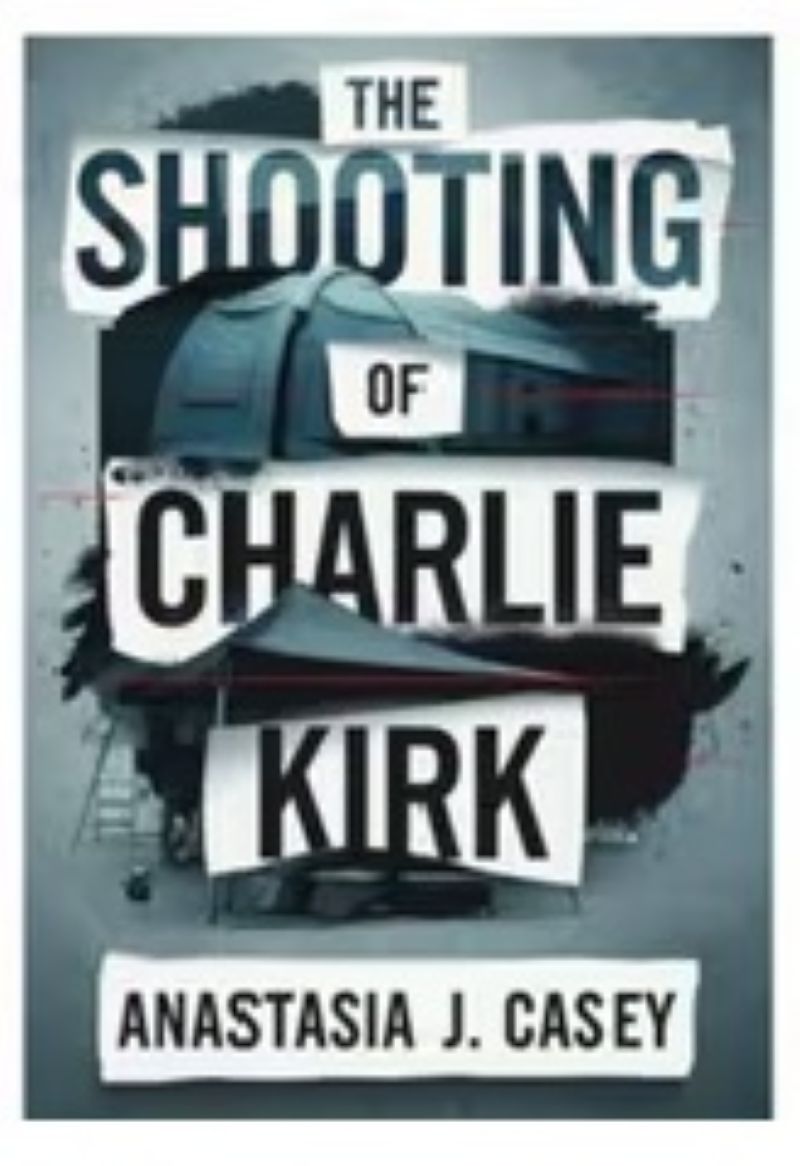



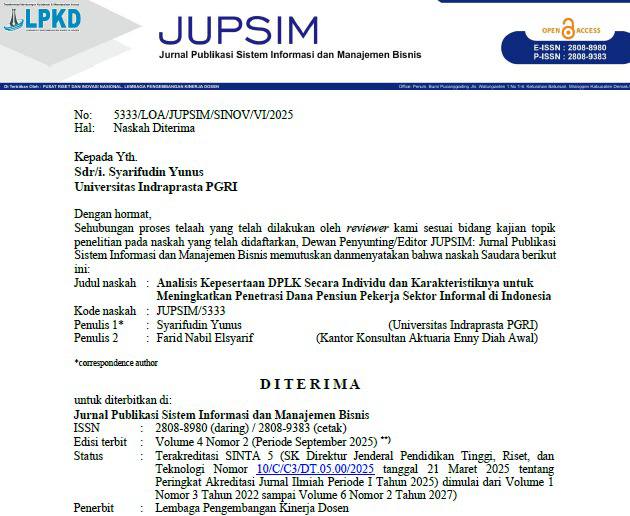


 96
96 0
0